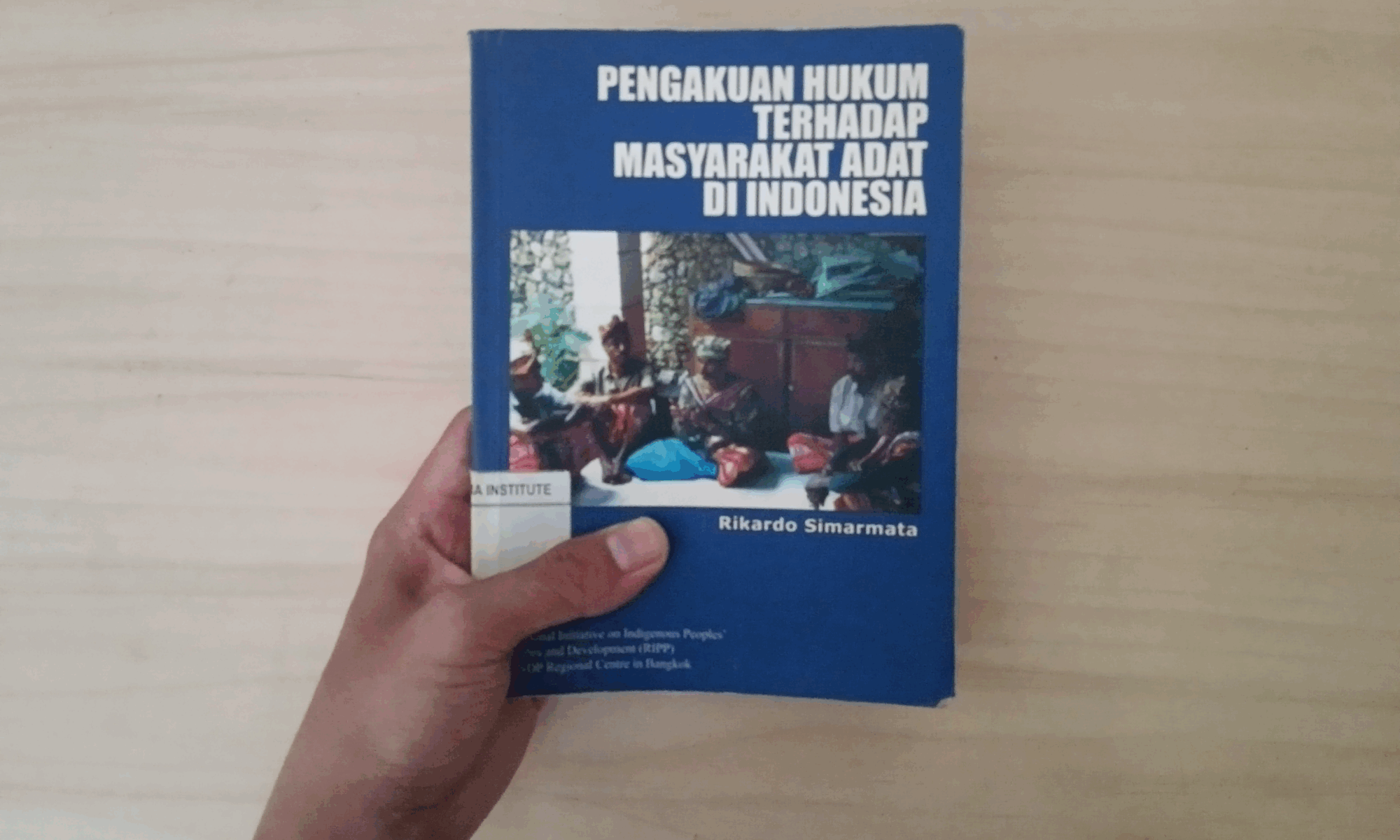- Judul: Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia
- Penulis: Rikardo Simarmata
- Penerbit: Regional Initiative on Indegenous Peoples Right and Development UNDP
- Tahun Terbit: 2006
- Halaman: x+375 halaman
Perdebatan mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum agrarian nasional sudah berlangsung lama. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menjadikan hukum adat sebagai dasar dan ukuran. Namun, ada juga yang menganggap hukum adat hanya sebagai pelengkap atau bahkan tidak sejalan sama sekali dengan hukum agrarian nasional.
Hazairin dan Mohammad Koesnoe adalah tokoh yang percaya bahwa UUPA dibangun di atas asas-asas hukum adat. Sebaliknya, Sudargo Gautama dan Boedi Harsono melihat hukum adat sebagai bagian yang harus disaring dari unsur kolonial dan feodal agar tidak mengganggu kepastian hukum. Bagi mereka, sifat hukum adat yang tidak tertulis dan beragam dianggap sebagai tantangan dalam membentuk hukum agrarian nasional yang seragam.
Dalam UUPA, istilah recognitie digunakan untuk menjelaskan hak yang diakui kepada masyarakat hukum adat, terutama ketika tanah ulayat mereka digunakan untuk pembangunan. Konsep ini sebenarnya diadopsi dari hukum adat, di mana seseorang yang bukan anggota persekutuan adat dapat menggunakan tanah ulayat dengan memberikan “hadiah” sebagai bentuk pengakuan atas hak milik adat.
Pengertian masyarakat hukum adat sendiri merujuk pada sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat dan tinggal bersama dalam suatu wilayah atau memiliki ikatan keturunan. Definisi ini muncul dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air dan UU Otsus Papua (otonomi khusus provinsi papua). Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari rechtsgemeenschap atau adatrechtsgemeenschap, dan mulai diperkenalkan oleh Van Vollenhoven serta diperluas oleh muridnya, Ter Haar.
Di sisi lain, istilah masyarakat adat lebih luas cakupannya. Muncul pertama kali melalui Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat (Japhama) pada 1993, istilah ini mencakup aspek nilai, politik, budaya, dan ekonomi. Istilah ini tidak sama persis dengan indigenous peoples seperti yang dijelaskan dalam Konvensi International Labour Organization 169, namun memiliki kemiripan. Pemakaian istilah masyarakat adat dianggap memberikan pendekatan yang lebih holistik dibanding masyarakat hukum adat yang cenderung berfokus pada aspek hukum semata.
Dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Misalnya, UU Kehutanan dan UU HAM menggunakan istilah masyarakat hukum adat, sedangkan UU Sistem Pendidikan Nasional dan UU Panas Bumi menggunakan istilah masyarakat adat. Selain itu, istilah komunitas adat terpencil (KAT) juga diperkenalkan melalui Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 sebagai pengganti istilah masyarakat terasing, yang merujuk pada kelompok sosial yang terpencar dan belum terintegrasi dalam sistem sosial, ekonomi, atau politik.
Sejarah Hukum Adat di Indonesia
Pada masa Hindia Belanda, hukum adat diakui keberadaannya, tetapi pengakuan ini dibagi dalam tiga aspek: hukum adat, peradilan adat, dan persekutuan hukum adat. Ketiganya diatur secara terpisah dalam berbagai regulasi. Pengakuan terhadap hukum adat secara formal dimulai pada tahun 1848 melalui Pasal 11 AB, yang menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi pribumi selama tidak bertentangan dengan asas keadilan umum versi kolonial. Pengakuan ini diperkuat lewat Regerings Reglement tahun 1854 dan Indische Staatsregeling (IS) tahun 1920, yang mengharuskan hakim memakai hukum adat jika tidak ada hukum tertulis, asalkan tetap selaras dengan prinsip keadilan Eropa.
Peradilan adat juga diakui dalam beberapa wilayah, khususnya di luar Jawa dan Madura, melalui Staatsblad 1932 dan pasal-pasal dalam IS. Di wilayah ini, masyarakat diizinkan menyelesaikan perkara pidana dan perdata melalui sistem peradilan adat. Namun, sejak 1935, peradilan adat ditempatkan di bawah pengawasan peradilan kolonial (Landraad), dan keputusan pengadilan desa dijadikan referensi sebelum perkara dinaikkan ke pengadilan resmi.
Konsep persekutuan hukum adat diperkenalkan oleh ilmuwan seperti Van Vollenhoven dan Ter Haar, yang menekankan bahwa masyarakat adat adalah kesatuan yang memiliki struktur, pemimpin, dan kekayaan bersama.
Desa di Jawa, nagari di Minangkabau, atau marga di Sumatera adalah contoh bentuk persekutuan hukum. Meskipun istilah tersebut tidak secara eksplisit masuk dalam peraturan kolonial, pengaturannya tersirat dalam kebijakan pemerintahan desa (Inlandsche Gemeente) yang disempurnakan melalui Inlandsche Gemeente Ordonantie tahun 1906 dan Inlandsche Gemeente Ordonantie Biutengewsten tahun 1938. Desa mulai diakui sebagai badan hukum dengan hak mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya.
Namun, pengakuan terhadap hak tanah adat menjadi persoalan besar. UU agraria (Agrarische Wet) tahun 1870 semula dimaksudkan untuk melindungi hak pribumi, namun kemudian dikebiri dengan diterbitkannya Agrarische Besluit yang menetapkan domein verklaring yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai milik pribadi menjadi milik negara. Akibatnya, tanah ulayat masyarakat adat dinyatakan sebagai tanah negara, kecuali jika diubah statusnya melalui proses hukum yang panjang dan rumit.
Intinya, pengakuan hukum terhadap adat di era kolonial hanyalah bentuk pengakuan bersyarat. Hukum adat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Eropa. Pemerintah kolonial tetap menjadi pengendali utama dan tidak sungguh-sungguh memberikan ruang otonomi pada masyarakat adat. Bahkan, tokoh seperti Stamford Raffles dan Van den Bosch memandang hukum adat sebagai inferior, lunak, dan bisa dibentuk sesuai kehendak pemerintah kolonial.
Sejak awal kemerdekaan, gagasan tentang pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah muncul dalam sidang-sidang pendirian negara. Pada Sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tokoh seperti Muhammad Yamin dan Soepomo sudah menyampaikan pentingnya desa, nagari, dan marga sebagai bagian dari susunan pemerintahan bawah. Yamin menyarankan agar desa dan satuan tradisional lainnya tetap diakui, meski perlu disesuaikan dengan zaman. Soepomo, yang menyusun kerangka Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menekankan bahwa negara harus menghormati daerah-daerah yang memiliki susunan asli, tanpa menganggap mereka sebagai negara dalam negara.
Pengaruh pemikiran Soepomo tampak dalam Pasal 18 UUD 1945 versi awal, yang mengakui keberadaan daerah-daerah swapraja (zelfbesturende landschappen) dan komunitas asli (volksgemeenschappen) seperti desa dan nagari. Meskipun begitu, istilah yang digunakan bukan rechtsgemeenschappen (persekutuan hukum), melainkan volksgemeenschappen, yang lebih berorientasi pada struktur administratif lokal.
Ketika UUD 1945 diganti oleh Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950, terjadi perubahan redaksional. Istilah “daerah yang bersifat istimewa” menjadi “daerah istimewa”, dan fokusnya hanya pada daerah swapraja, bukan lagi komunitas adat. Meski demikian, substansi pengakuan tetap ada. Pasal 146 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Pasal 104 UUD Sementara juga memberikan dasar hukum untuk memberlakukan hukum adat dalam sistem peradilan.
Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat mulai menguat setelah kemerdekaan, terutama melalui UUPA 1960 yang mengakui hak ulayat sebagai dasar hak atas tanah bagi masyarakat adat. Pengakuan ini diberikan dengan syarat: hak ulayat masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, UUPA menegaskan bahwa tanah, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara sebagai milik bangsa Indonesia. Hal ini menjadikan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah, menggantikan posisi kepala adat, dan membatasi pelaksanaan hak ulayat agar tidak menghambat pembangunan nasional, termasuk pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan program transmigrasi.
Pada masa Orde Baru, perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat semakin berkurang karena orientasi pemerintah berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Program landreform dibekukan karena dicurigai sebagai agenda kelompok kiri. Sebagai gantinya, negara membuka ruang investasi melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan sejumlah UU sektoral seperti Kehutanan dan Pertambangan tahun 1967. UU ini tetap meniru pendekatan UUPA dengan menjunjung tinggi Hak Menguasai Negara (HMN) dan hanya mengakui hak ulayat secara terbatas. Hutan adat dan wilayah adat lainnya bahkan dikategorikan sebagai milik negara, dan keberadaannya secara hukum dianggap tidak ada demi kepentingan eksploitasi sumber daya alam.
Di sisi lain, UUPA dan undang-undang sektoral juga mendorong unifikasi hukum nasional. Hukum adat dianggap sebagai hambatan terhadap kepastian hukum karena dinilai terlalu terpengaruh oleh sistem kolonial dan feodal. Oleh karena itu, hanya hukum adat yang telah “disempurnakan” yang bisa diakui dalam sistem hukum nasional. Hukum adat versi ini disebut sebagai hukum adat modern atau nasional, yaitu hukum adat yang telah kehilangan sifat kedaerahan dan diubah agar sesuai dengan sistem hukum yang berlaku secara nasional.
Runtuhnya Orde Baru pada 1998 dipicu krisis ekonomi parah yang melumpuhkan perekonomian nasional, nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga naik tajam, dan pengangguran meluas. Gelombang demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 20 Mei 1998, dan Wakil Presiden B.J. Habibie naik menggantikannya. Dalam masa transisi, Habibie meluncurkan sejumlah kebijakan reformasi, seperti revisi UU Partai Politik dan Pemilu, serta pengesahan UU Pemerintahan Daerah dan UU Kehutanan pada 1999. Namun, laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR, dan Abdurrahman Wahid kemudian terpilih menjadi presiden melalui Sidang Istimewa MPR.
Pada tahun 2000 turut dilakukan amandemen kedua UUD 1945 untuk memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai perkembangan zaman.
Namun, amandemen ini juga membawa perubahan penting. Pengakuan tidak lagi diberikan secara mutlak, melainkan disertai syarat-syarat tertentu. Di samping itu, satuan masyarakat adat seperti desa dan nagari tidak lagi dianggap sebagai daerah istimewa, kecuali yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan. Istilah “pengakuan” pun mulai digunakan secara eksplisit, mendampingi istilah “penghormatan”, menandai perubahan pendekatan negara terhadap hak-hak masyarakat adat.
Proses reformasi membawa perubahan signifikan dalam penyusunan undang-undang, yang kini mulai melibatkan masyarakat sipil. Contohnya adalah pembentukan Komite Reformasi Pembangunan Kehutanan yang menyusun RUU Kehutanan dengan melibatkan birokrat, akademisi, dan aktivis. Reformasi ini juga dipicu oleh kritik luas terhadap kegagalan pengelolaan sumber daya alam oleh Orde Baru yang eksploitatif dan terpusat. Deforestasi besar-besaran terjadi akibat konsesi Hak Penguasaan Hutan yang dikuasai kroni penguasa, sementara kerusakan lingkungan juga meluas akibat praktik pertambangan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.
Upaya Mengakui Masyarakat Hukum Adat
UU No. 22/1999 menjadi tonggak awal pengakuan kembali masyarakat hukum adat setelah 30 tahun penyeragaman. UU ini membolehkan penggunaan istilah lokal seperti nagari, marga, atau kampung, dan mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan otonom. Pengaturan adat istiadat diperkuat dengan kewajiban bagi kepala desa dan lembaga desa untuk menghormati nilai-nilai adat setempat. Meski ada revisi dalam UU No. 32/2004 yang mencabut beberapa kewenangan adat, undang-undang ini tetap memuat klausul pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan diakui melalui peraturan daerah.
UU HAM dan UU Kehutanan (No. 41/1999) memperkuat dasar hukum pengakuan hak-hak kolektif masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat. Meskipun UU Kehutanan mengakui keberadaan hutan adat, hutan tersebut tetap dianggap sebagai bagian dari hutan negara dan hanya dapat dikelola oleh masyarakat adat jika keberadaannya diakui secara formal lewat Perda. Pengakuan tersebut harus memenuhi lima unsur seperti adanya struktur adat, wilayah hukum jelas, dan praktek hukum adat yang masih ditaati.
Untuk memperjelas pengakuan hak ulayat, dikeluarkan Permen Agraria No. 5 Tahun 1999 yang mengatur prosedur identifikasi, pemetaan, dan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah. Masyarakat hukum adat tidak harus berasal dari satu suku, tetapi merupakan komunitas yang hidup bersama dalam tatanan hukum adat yang sama. Di sisi lain, amandemen kedua UUD 1945 (Pasal 18B dan 28I) menjadi landasan konstitusional penting dalam memperkuat kedudukan hukum masyarakat adat. Ini diperkuat oleh Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 yang mewajibkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan SDA.
Pengakuan masyarakat hukum adat semakin luas dan merambah ke berbagai sektor seperti pendidikan, peradilan, minyak dan gas, panas bumi, hingga perikanan. UU No. 20/2003 tentang Pendidikan Nasional menjamin layanan khusus untuk masyarakat adat, dan UU MK mengakui masyarakat adat sebagai pihak yang bisa mengajukan uji materi. Tahun 2004 ditandai dengan lahirnya UU Sumber Daya Air, Perkebunan, dan Perikanan yang juga mengakui hak-hak adat. Ditambah lagi, ratifikasi Kovenan Internasional melalui UU No. 11 dan 12 Tahun 2005 memberikan penguatan internasional atas hak-hak masyarakat adat, termasuk hak menentukan nasib sendiri, hak atas pendidikan, kesehatan, dan penghidupan layak, baik secara individu maupun kolektif.
Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia mengalami banyak perubahan. Pada awalnya, UUD 1945 sebelum amandemen mengakui masyarakat adat secara penuh tanpa syarat. Namun setelah amandemen, pengakuan itu menjadi bersyarat. Artinya, masyarakat adat hanya diakui jika mereka masih hidup, sesuai dengan perkembangan zaman, dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta hukum yang berlaku. Perubahan ini menunjukkan kehati-hatian negara dalam mengelola isu adat agar tidak menimbulkan konflik sosial atau mengganggu integrasi nasional.
Dalam peraturan sektoral seperti UUPA, UU Kehutanan, dan UU Sumber Daya Air, masyarakat adat diakui jika memiliki hak ulayat dan sistem hukum adat yang jelas. Ini berarti mereka harus memiliki wilayah, lembaga adat, dan hukum adat yang masih dijalankan. Di sisi lain, dalam UU Pemerintahan Daerah dan Desa, pengakuan lebih fokus pada kelembagaan adat saja, tanpa memperhatikan wilayah atau hak atas sumber daya alam. Hal ini membuat pengakuan masyarakat adat menjadi sempit dan terbatas.
Setelah reformasi, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak ulayat mereka. Beberapa daerah seperti Kampar, Lebak, dan Nunukan telah mengeluarkan perda untuk mengatur ini. Ada dua pendekatan utama: ada yang menetapkan hak ulayat berdasarkan kebutuhan pembangunan, dan ada pula yang memetakan tanah ulayat berdasarkan pengakuan masyarakat. Di Papua dan Sumatera Barat, pengakuan dilakukan melalui penelitian dan pemetaan, meskipun belum semua melibatkan tokoh adat atau LSM, sebagaimana disarankan dalam aturan pusat.
Praktik pengakuan ini juga berbeda-beda, terutama ketika tanah ulayat berada di kawasan hutan negara. Ada daerah yang menganggap wilayah tersebut harus tetap dikelola oleh negara, ada pula yang mengakui hak masyarakat adat dengan tetap mematuhi aturan nasional. Namun pada dasarnya, pengakuan terhadap hak ulayat belum otomatis menjadikannya sebagai hutan adat; harus melalui proses hukum tambahan dan pengukuhan oleh pemerintah daerah.
Banyak daerah memanfaatkan ruang yang diberikan oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 76 Tahun 2001 untuk mengatur sistem pemerintahan lokal berbasis adat. Contohnya, Sumatera Barat menghidupkan kembali sistem nagari yang mengatur pemerintahan adat secara penuh, termasuk kepemimpinan dan pelayanan publik. Daerah lain seperti Tana Toraja menggunakan istilah “lembang”, dan Sanggau memakai “kampung”. Di Aceh, mukim dihidupkan kembali, sementara di Bali, desa pakraman diakui sebagai masyarakat hukum adat.
Pengakuan terhadap lembaga adat juga menjadi bagian penting dalam pengakuan masyarakat adat. Beberapa daerah seperti Aceh dan Sumatera Barat telah memiliki perda atau keputusan kepala daerah yang mengatur lembaga adat. Di Aceh, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) berubah menjadi Majelis Adat Aceh (MAA), yang diakui secara formal.
Penulis: Laura Salma Afriyanti