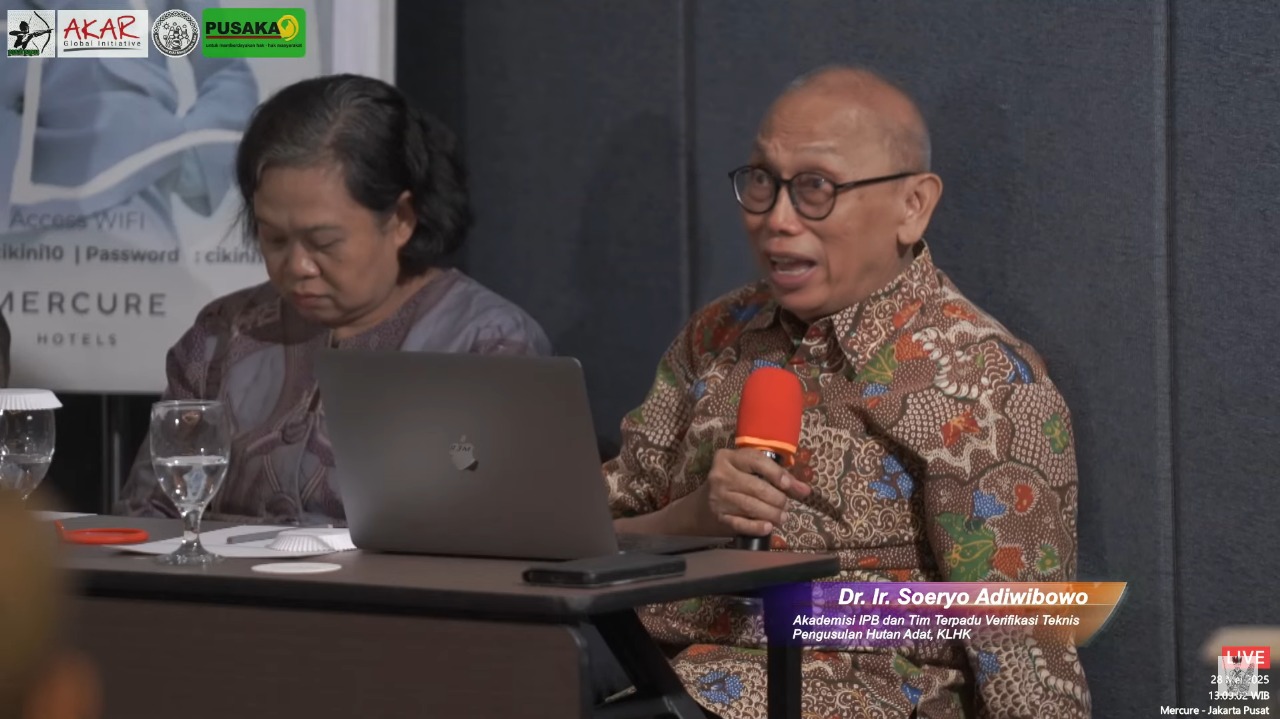Rabu (28/5), diskusi bertajuk “Diskusi Pengakuan Hampa : Evaluasi Pengakuan MA Papua dalam 10 Tahun Rezim Pembangunan Presiden Jokowi”, dilaksanakan di Mercure Hotel Cikini, Jl. Cikini Raya No.66, Jakarta. Pada diskusi ini turut menghadirkan beberapa narasumber antara lain Nur Amalia (Eco-Adat dan Perwakilan Koalisasi Kawal Rancangan Undang-Undangan Masyarakat Adat), Agung Wibowo (Koordinator Perkumpulan HuMa), Soeryo Adiwibowo (Akademisi IPB dan Tim Terpadu Verifikasi Teknis Pengusulan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan), Yance Arizona ( Dosen FH UGM), Yuli Prasetyo Nugroho (Direktorat PKTHA, Ditjen PSKL Kementerian Kehutanan), dan dimoderatori oleh Paramita Iswari.
Nur Amalia membuka diskusi dengan menyampaikan Selama satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, pengakuan terhadap masyarakat adat, khususnya di Papua, menunjukkan kemajuan yang stagnan. “Walaupun konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) secara eksplisit mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat, kenyataannya belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur dan melindungi mereka”, ucap Nur.
Menurut Nur Amalia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat. Berbagai aturan sektoral, seperti Undang-Undang Kehutanan Pasal 67 dan Permendagri No. 52 Tahun 2014, masih mewajibkan adanya pengakuan melalui peraturan daerah, yang seringkali sulit dicapai karena birokrasi dan minimnya dukungan politik. “Alhasil, pengakuan terhadap hak adat lebih banyak berhenti pada tataran administratif dan simbolik, tanpa implementasi nyata yang melindungi hak atas tanah, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hukum adat masyarakat”, tambah Nur.
Nur Amalia juga mengatakan, bahwa ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Adat yang bersifat lex specialis menjadi hambatan serius dalam menjamin keadilan dan kesetaraan bagi komunitas adat, terutama di wilayah seperti Papua yang memiliki status otonomi khusus. Padahal secara filosofis, keberadaan masyarakat adat adalah bagian dari kekayaan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut Nur Amalia saat ini masih banyak diskriminasi dan pelanggaran hak yang terjadi, seperti hilangnya hak pilih karena tidak tercatat dalam administrasi negara, serta diskriminalisasi atas praktik adat seperti peladangan tradisional. Secara yuridis, puluhan regulasi telah menyebut dan mengatur masyarakat adat, namun tidak satu pun memberikan perlindungan yang utuh. “Oleh karena itu, dorongan untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat sangat mendesak, agar hak-hak dasar seperti pengakuan, perlindungan hukum, dan pelibatan penuh dalam proses pembangunan dapat diwujudkan”, tandas Nur.
Agung Wibowo memaparkan pendapatnya, bahwa sejak tahun 2008 masyarakat adat di Kapuas Hulu telah memperjuangkan pengakuan hukum atas keberadaan dan hak melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang pengakuan masyarakat adat. Meski perjuangan panjang ini sudah sampai pada tahap pengusulan penetapan hutan adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), prosesnya masih kerap mengalami hambatan.
“Salah satu contoh nyata adalah pembatalan mendadak penyerahan SK Hutan Adat oleh Presiden yang seharusnya dilakukan di Putussibau. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun penetapan hutan adat di masa pemerintahan Prabowo, yang menunjukkan stagnasi dalam pengakuan hak masyarakat adat”, tambah Agung.
Menurut Agung, perjuangan masyarakat adat untuk mendapat pengakuan tidaklah mudah. Harus ada mobilisasi sistem hukum adat dan upaya membentuk produk hukum formal seperti Perda, Peraturan Gubernur, SK Bupati, hingga mengakses jalur hukum lain yang tersedia, yang jumlahnya kini mencapai 461 produk hukum di Indonesia.
Pada kasus di masyarakat adat Papua memiliki jalur khusus melalui UU Otonomi Khusus (Otsus) dan Peraturan Daerah Khusus. Namun, pengakuan ini tetap menghadapi banyak tantangan, baik dari segi subjek maupun objek hukum. “Ironisnya, nilai-nilai lokal seperti tradisi menimang anak di hutan, musik tradisional, dan hutan sebagai ruang kehidupan anak-anak jarang dijadikan pertimbangan dalam kebijakan, padahal semua itu adalah bagian dari sumber hukum dan identitas masyarakat yang semestinya dihargai dan dilindungi negara”, ujar Agung.
Dalam konteks masalah pengakuan hutan adat di Papua, Yance Arizona berpendapat soal keterkaitannya pengakuan masyarakat adat Papua dengan persoalan integrasi, kekerasan dan pelanggaran HAM, marginalisasi ekonomi, diskriminasi rasial, serta konflik sumber daya. Pemerintah pusat menawarkan Otsus sebagai solusi yang diwujudkan melalui dana khusus, pemekaran provinsi, dan beberapa Perdasus terkait hak ulayat, pengelolaan hutan, dan peradilan adat.
Namun, dalam praktiknya, Otsus dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di Papua. “Banyak peraturan yang seharusnya menguatkan posisi masyarakat adat justru melemah karena tumpang tindih dengan regulasi nasional yang lebih kuat, serta tidak adanya peraturan teknis yang berpihak kepada konteks kekhususan Papua”, kata Yance.
Menurut Yance, Refleksi terhadap Putusan MK No. 35 tahun 2012 yang mengubah definisi hutan adat dari “hutan negara” menjadi milik masyarakat hukum adat, menunjukkan bahwa kendali negara masih sangat dominan. Dalam praktiknya, pengakuan hutan adat justru ditentukan melalui serangkaian proses birokratis yang kompleks dan tidak setara, menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang lemah.
“Pengakuan hutan adat di Papua sebaiknya tidak lagi memerlukan SK atau Perda tambahan karena identitas adat sudah melekat melalui UU Otsus, melainkan cukup dengan melihat realitas penguasaan masyarakat terhadap wilayahnya sebagai dasar pengakuan”, tambah Yance.
Di sesi pemaparan akhir Soeryo Adiwibowo menambahkan, bahwa pengakuan Hukum Adat di papua juga masih sangat terbatas di banding provinsi lain. Terdapat beberapa persoalan yang harus dihadapi. “Diantaranya yaitu hukum adat digolongkan sebagai bagian perhutanan sosial, kompleksitas “kewenangan” antar Kementerian, dan RUU MA yang masih tersendat bahkan cenderung macet”, ujar Soeryo.
Soeryo juga menyoroti aspek kritik saat verifikasi hutan adat yang dihadapi yaitu penerapan metode verifikasi berbasis ilmiah (science based verification). Namun menurut Soeryo tantangan verifikasi menghadapi banyak keterbatasan sumber daya. “Saat ini, tenaga besar sudah dicurahkan oleh Kementerian antara lain untuk program satu hari untuk verifikasi satu wilayah adat dan hutan adat, lokakarya, dan legitimasi multi-pihak”, tandas Soeryo.
Penulis: Laura Salma Afrianti